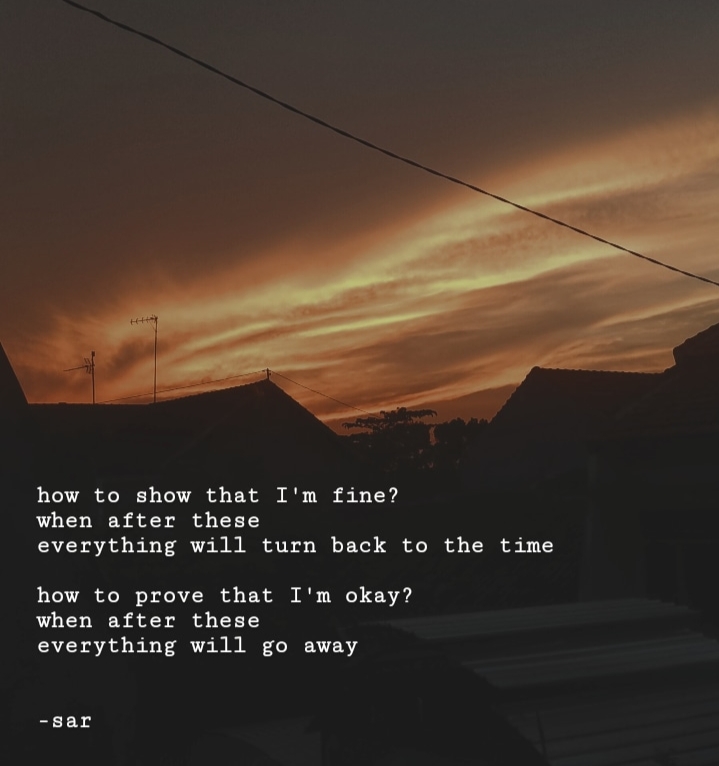|
| Sumber gambar: Pak Wahyu, guru SMA penulis |
Berambut hitam, berusaha menjadi yang dia idamkan. Nongkrong di warung
dekat sekolahan, meng-update varian baru minuman sachet-an.
Sengaja berlama-lama, menunggu ia lewat bersama kawan lainnya. Nah, itu dia. Eh, ada yang beda. Sore ini ia berjalan sendiri. Menenteng tas plastik berisi sebungkus nasi,
wajahnya pucat pasi menatap alas kaki. Aku ingin menyapa, tapi sadar aku siapa.
Hari ini hari apa? Hari Rabu, bukan jadwalnya puasa. Lalu hari apa? Oh! Ini hari pengumpulan nilai sebelum pemilihan jurusan kuliah, tapi dia ada apa? Bukankah nilainya baik-baik saja? Yah, setidaknya
daripada aku.
Mungkin dia bingung memilih jurusan kuliah. Hmm, kuliah. Sudah lama juga ya
aku mengamatinya, tapi saling bicara baru sekali saja. Kala itu, aku bertugas
sebagai panitia. Kini aku ingin dia melihatku sebagai seorang pria. Namun, bagaimana? Masa iya aku harus satu
kampus dengannya? Entahlah.
Eh, ada apa itu ramai-ramai? Kecelakaan? Putri? Astaga, dia kecelakaan!
Belum lunas mi ayam kubayar, aku menggendong tas lalu lari. Dia sudah
dikerumuni banyak orang. Dia masih sadar, tidak menangis, tapi tampak kaget.
Bapak-bapak yang menyerempetnya masih marah-marah, mengomeli Putri. Pandangan
mata Putri kosong. Dia tampak menyedihkan. Aku tidak mendekatinya karena aku
takut ia makin kalut, toh mungkin dia sudah lupa aku siapa. Aku memungut tas
plastik berisi sebungkus nasi lalu kubuang ke tempat sampah karena sudah tak
layak makan. Putri diantar pulang ke kosnya oleh mbak-mbak dan ibu-ibu.
Alih-alih ikut, aku balik kanan dan pergi.
Aku harus bayar mi ayamku tadi. Setelah itu, pergi ke warung nasi. Buat
apa? Buat Putrilah, dia mungkin lupa nasinya sudah tiada. Eh, ini apa? Berani sekali aku
tiba-tiba. Tidak apa, toh seragamku masih sama dengannya. Aku tidak asing-asing
amat. Mungkin juga ini
tahun terakhir aku melihatnya. Aku tidak akan mendengar kebisingan kepala yang
jahat kali ini.
"Permisi, Bu, Mbak. Saya satu sekolah sama Putri. Saya mau ngasih ini. Nasi dia
tadi jatuh dan terlanjur kotor pas kecelakaan," ucapku menarik perhatian
ibu-ibu dan mbak-mbak.
"Kamu kenal anak ini, Nduk?" tanya seorang ibu pada Putri. Masih dengan
wajah lemas, Putri menggeleng kepala.
"Eh, mungkin Putri lupa, Bu, karena saya nggak sekelas juga sama dia.
Salam kenal, Put. Nama saya Budi. Tadi nggak sengaja lihat orang satu
seragam dengan saya kecelakaan dan mungkin ini bisa membantu Putri,"
terangku penuh canggung sambil menyodorkan nasi.
"Oalah, Le. Ya udah taruh sini saja, ini Mbak e masih shock,"
jawab seorang ibu tadi.
"Kalau gitu, saya pamit dulu, ya, Bu. Mari, Bu, Mbak.
Cepet pulih ya, Put. Mari," pamitku dibuntuti deru sepeda motor.
Selama perjalanan pulang, aku senyum-senyum sendiri di dalam helm, mengagumi keberanianku
hari ini. Astaga, aku kok malah senang padahal dia baru saja ditimpa celaka.
Tenang, tenang. Duh, tapi tetap saja ada gejolak senang! Yah, lumayan, setidaknya ada kemajuan.
Esoknya, aku tidak menemukan Putri di sekolah. Mungkin dia berdiam di kelas
atau entahlah. Pulang sekolah, aku mampir lagi ke warung mi untuk mengecek
kondisi. Alih-alih mengamati Putri dari jauh, aku malah menemukannya di warung
mi. Stay cool, aku memesan minum lalu memilih duduk jarak dua kursi dengannya.
Dia tidak pakai seragam, tapi pakai jaket dan celana training.
Dia tampak lebih baik dari kemarin, tapi pandangannya tampak malas seraya
bermain gawai. Mi ayamnya datang, Putri mendongak. Selayang pandang tertuju
padaku, alisnya naik satu. Aku yang agak tersapu, eh tersipu, diselamatkan
minumanku yang juga baru datang. Gelagapan
aku menerima segelas minuman dari ibu pemilik warung. Mampus aku salah tingkah.
Kulipat kedua lenganku jadi satu di atas meja. Aku bergerak setenang yang
kubisa, memasang wajah senormal-normalnya. Kutenggelamkan kepala. Duh, sudah
tiada wajah aku.
Saat kita berserah, saat itulah semesta bekerja.
Kutipan dari buku karya Marchella FP itu sedang berpihak padaku. Tanpa diduga, dia angkat bicara.
"Kamu yang bawa nasi kemarin sore ya? Siapa namamu? Budi, ya?"
Sontak aku mengangkat kepala dan berkata, "Eh, oh iya, iya, bener. Masih inget ya ternyata."
"Aku lumayan kaget lo, kamu tahu namaku. Makasih ya. Habis berapa
nasinya?"
"Ngga usah, ngga usah. Ngga usah diganti. Udah, santailah."
Aku tersenyum sebaik mungkin, ia mengikuti. Percakapan
pertama setelah dua tahun lalu terjadi kembali. Sesudah itu, mi ayamku datang.
Putri memilih menghabiskan mi ayamnya dalam diam, aku mengikuti.
Semenjak h+1 kecelakaan itu, aku dan Putri sering bertegur sapa bila
bertemu, saling mengirim pesan, saling bertanya PR meski kadang modusku
saja. Meski responnya
lambat, Putri masih membalas pesanku yang singkat. Entah apa yang dipikirkannya
sampai ia mau membaca pesanku. Yah, setidaknya aku bisa merasakan ke-uwu-an
yang sering diceritakan kawan-kawan. Namun, keadaan ini belum membuatku berani
menawarkan diri menjadi tempat cerita privasinya berlabuh. Padahal dalam hati,
mata dan telingaku siap kapanpun ia berkeluh. Jadilah aku belum menemukan
jawaban dari wajah sendunya siang itu. Tak apa. Aku mengapresiasi perkembangan
pesatku dua minggu terakhir ini.
"Bud, yok!" kata Rio tiba-tiba. Aku akan pulang bersama
Rio sore ini karena Rio bilang ingin nebeng untuk beli seblak di belakang gedung olahraga. Sesaat sebelum kakiku naik motor, arah mataku
parkir di sudut pertigaan dekat sekolah. Siapa itu yang tampak membeli
buah?
Putri terlihat memandang ke arahku, tapi wajahnya datar. Bukan, bukan aku.
Dari tempatku berdiri, matanya tampak melihat sisi kiriku. Aku tengok ke
belakang. Tiada yang spesial, hanya beberapa murid sedang menunggu jemputan.
Ada juga seorang siswi yang mencium tangan ayahnya lalu duduk ke atas sepeda motor. Kulihat depan
lagi, Putri sudah tiada di dekat gerobak rujak tadi.
"Eh, anu, duluan aja, Bro. Ntar kalau udah kelar beli seblak, taruh
aja motor gue di warung mi ayam sebelah sekolah," ucapku pada Rio.
"Lah, nanti gue pulang tetep jalan dong," keluh
Rio.
"Duh, gimana
ya. Ya udah deh, nanti dari warung mi, gue tebengin lu sampe rumah.
Sekarang gue ada urusan bentar nih, mendadak. Dah, sana, ati-ati," ucapku pada
kawan sekelasku itu lalu pergi.
Aku berhasil menyamai langkah kaki Putri. Dia menemuiku dengan sorot mata
ramah. Rencananya, aku akan mengajaknya makan mi ayam, tapi katanya ia ingin makan nasi
sayur. Jadilah aku si anak micin ikut mengonsumsi klorofil.
"Nasi yang dulu itu, aku beli di sini juga," kataku sambil mengisi waktu antre
makan.
"Wah bagus ya, udah hafal langganan kuliner anak kos sini," balas
Putri.
"Oh, ya, jelas. Soalnya temenku sekelas ada empat anak, mereka ngekos semua. Jadi tahu deh.
Ngomong-ngomong, kenapa kamu ngga sekolah di deket rumah aja, Put?" terangku.
"Pertanyaan sejuta umat. Ya, ngga apa-apa sih nyoba di sini."
"Kamu ngga kangen keluarga di rumah gitu?"
"Pertanyaan setengah juta umat. Ya kangenlah, tapi kelamaan juga biasa
aja. Kenapa tiba-tiba nanya gitu?"
"Ngga ada apa-apa sih. Tadi ngga sengaja liat kamu pas beli buah di
sana, kamu lagi nengok ke arah cewek yang dijemput bapaknya gitu. Kali aja lagi homesick. Homesick ya?"
"Oalah. Ngga homesick juga sih, tapi keinget aja dulu
pas masih zaman dianter Bapak ke sekolah, biasanya salim Bapak dulu. Sekarang
ya, paling kalau pas pulang ke
rumah aja."
Entah apa yang merasukiku, aku menepuk-nepuk kepalanya yang dibalut
kerudung putih sambil berkata, "Ya udah, ngga apa-apa. Besok Sabtu bisa
pulang."
Byar. Meledaklah kecanggungan di antara kami. Dia balik kanan dan aku baru
menyadari antrean makan sudah sepi. Dia memesan makanan untuk dua orang dan
duduk kembali. Fyuh. Aku merasa lega ia tidak bertanya kenapa-napa.
"Nih nasi bayem. Ngga apa-apa, kan?" tanya Putri.
"Ngga apa-apa. Makasih dipesenin," balasku se-cool mungkin.
"Oke, sans. Eh,
tadi kenapa tiba-tiba tanganmu mendarat di kepalaku?"
Duh, dia pake nyinggung juga. "Eh, sorry, tapi kalau mendarat di tanganmu kan bukan mahram."
Dia tersenyum
tipis lalu membalas, "Halah modus."
"Hehehehe. Besok Sabtu kamu pulang ngga?" tanyaku
sambil mulai menyendok nasi.
"Belum tahu, agak gimana gitu kayanya kalau pulang ke rumah besok."
"Boleh tahu kenapa?"
Dia menghentikan makannya sebentar, melihatku dua detik, lalu kembali melihat piring. Aku membaca air mukanya dan lebih dulu
berkata, "Kalau ngga mau cerita juga ga apa-apa kok. Santai, Put."
"Eh, bukan gitu sih, tapi maaf nih jadi curcol. Jadi aku lagi galau-galaunya milih jurusan
kuliah, sedangkan bapakku terus nanyain aku milih jurusan apa. Ya gimana ya, kesel aja
ditanyain terus."
“Emang jurusan yang kamu galauin apa?”
“Banyak, soalnya makin SMA ini, kuitung cita-citaku
ada banyak. Terus ya, akhir-akhir ini aku sering banget denger kalau nyari
jurusan kuliah itu yang sesuai passion. Nah masalahnya, aku belum
tahu jelas nih passion-ku apa. Kalau kamu mau masuk jurusan apa,
Bud?" jawabnya sebelum menyuap nasi.
“Aku mau masuk pendidikan dokter."
"Wuih, keren. Pantes
kamu belajar keras gitu ya, sampe nanya-nanya soal ke aku."
Duh, dia mulai membahas alibi modusku. Aku
membalas, "Eh, ya, gitulah, tapi kamu masih jauh lebih pinter
sih. Aku yakin kamu berhasil masuk jurusan pilihanmu nanti."
Dia menghentikan makannya sebentar, melihatku dua detik, lalu bertanya, “Kamu ngga takut ya, Bud?"
Aku menghentikan makanku sebentar, baru menjawab, “Takut?”
“Iya, takut. Takut gagal masuk jurusan pilihanmu.
Takut ngga?”
“Hmm, kalau takut, ada sih. Kemungkinan ngga diterima
kan juga pasti ada, tapi seenggaknya aku udah berusaha dan berdoa yang terbaik
buat masuk ke sana. Emang kenapa? Kamu galau karena kamu takut?”
Dia menelan makanan di mulutnya, lalu berkata, “Jujur,
iya, Bud. Mungkin saking takutnya, aku jadi ngga berani milih jurusan yang
menurutku susah. Terus kenapa ya orang-orang kalau kutanyain kaya kamu tadi,
jawabnya kebanyakan tuh intinya do your best, God will do the rest. Kenapa
ngga, ya udah realistis aja sesuai kemampuan yang ada gitu daripada nantinya
kecewa, kan ya semua orang tahu kan kapasitas dirinya masing-masing.”
Aku menelan suapan nasi terakhirku. Makananku sudah
kandas, obrolan ini mulai panas. Aku menghela napas, menatap langit-langit
warung sambil berusaha membalas pernyataan Putri dengan pantas.
“Sayangnya beberapa orang belum tahu pasti kapasitas
dirinya, Put, termasuk aku. Aku merasa dengan menghadapi ujian seleksi nanti,
aku akan mengerti kapasitasku, seberapa layak aku mendapatkan yang kuinginkan.”
“Kalau gagal dapetin yang kamu inginkan gimana?”
“Hmm, kalau gagal, ya udah. Mungkin nanti aku akan
menjalani jurusan lain atau ikut lagi ujian tahun depan. Entahlah, sebenarnya
aku juga belum ngerti-ngerti amat, Put, passion-ku apa. Namun, yang
pasti, kalau aku udah berjuang, setidaknya ya emang aku udah berusaha. Kalaupun
gagal, toh aku udah nglakuin yang maksimal. Jadi, aku akan lebih menghargai
perjuanganku, Put, dengan memaafkan diri sendiri dan berjuang lagi untuk
hari-hari berikutnya.”
“Yah, pasrah amat, Bud, aku dengernya.”
“Ya mau gimana lagi, Put. Setelah beberapa kegagalan
kecil berlalu, aku ngga mau terlalu memaksakan apa mauku. Udah ngerti apa yang
kumau aja udah bersyukur banget, Put, tapi kan mauku itu belum tentu juga
mau-Nya Yang Maha Kuasa. Aku yakin kok Yang Maha Baik akan memberikan yang
terbaik di waktu yang terbaik pula. Minimal, aku berjuang supaya aku
ga nyesel-nyesel amat di kemudian hari, apapun hasil perjuangannya nanti.
Mantap deh, gue bisa bilang ginian.”
Pandangan mataku turun dari atap warung. Putri diam
seperti sedang mencerna kata-kataku dan makanannya yang sudah raib dari piring.
Aku tidak akan memaksanya mengerti sekarang juga. Aku bisa mengerti kalimatku
sendiri juga karena aku telah merasakannya bertahun-tahun. Rupanya ada juga
gunanya tahun-tahun penantian itu. Aku bicara tadi seakan sedang presentasi
menyampaikan hasil kerjaku hingga bisa duduk satu meja dengannya seperti saat
ini. Yah, mungkin kalimat tadi hanya dari mulut, tapi semoga hatimu paham, Put.
Tiba-tiba ponselku dalam saku berdering. Nomor ponsel
Rio terpampang di sana. Duh, aku baru ingat. Segera aku angkat telepon itu lalu
disambut suara menggebu-gebu berbunyi, “Heh, lu dimana sih, Bud? Dicariin di
warung mi ga ketemu-temu.”
“Eh, gue ngga jadi ke warung mi tadi. Sorry,
sorry. Lu dimana sekarang?”
“Gue di warung mi ayamlah. Lu dimana sih? Gue
samperin.”
“Eh jangan, jangan. Gue yang ke warung mi aja nih
sekarang, tunggu bentar di situ. Jangan kemana-mana.” Telepon kututup. Kulihat
Putri baru saja usai menangkupkan muka dengan tangannya. Ekspresinya berubah
saat melihatku tampak buru-buru.
“Put, sorry nih. Hmm, udah sore, aku
balik duluan ya,” ucapku setenang mungkin.
“Oh, iya ngga apa-apa. Makasih ya udah mau sharing,”
balasnya sambil tersenyum.
“Oke sama-sama. Dah, semangat ya, Put.” Aku beranjak
pergi.
“Eh, jangan lupa bayar dulu, Bud.”
Langkah kakiku mundur lagi. “Oiya, hampir lupa. Hehe.”
Pertemuan di warung nasi itu bagiku sudah cukup
menjawab kekhawatiranku pada wajah sendunya di siang itu. Entah dugaanku yang benar
atau tidak, tapi semenjak sore itu, Putri menjadi lebih terbuka denganku. Saat
kebetulan berjumpa di sekolah, kami saling sapa dengan suasana lebih cair dari
sebelumnya. Namun, aku banyak mendapat penolakan saat Putri kuajak makan
sepulang sekolah. Katanya, ia mau cepat pulang dan belajar. Yah, tak apa,
lagipula wajahnya jadi lebih sumringah dari sebelumnya. Ia tampak bergairah dan
hal itu menular padaku.
Ujian datang bertalu-talu hingga akhirnya kami resmi
lepas dari seragam putih abu-abu. Di satu sisi, ujian seleksi masuk
perguruan tinggi masih satu bulan lagi. Waktu wisuda bukan menjadi momentum
akhir perjuangan karir akademisku dan Putri. Namun, di hari puncak akhir masa
SMA ini, aku ingin sekali saja berfoto dengannya. Bukan apa-apa, tapi mungkin ini
menjadi hari terakhir aku bertemu dengan Putri, salah satu manusia yang
berandil cukup besar selama aku menghadapi SMA.
Aku berhasil beberapa kali menangkap pandang Putri
dengan kebaya merah muda. Namun, sampai acara wisuda usai, aku tidak sempat
mengabadikannya dalam kamera. Pesan singkat memang membuat kami dekat beberapa
bulan terakhir, tapi hal itu belum sempat membuatku berani mengajaknya foto
wisuda bersama sejak jauh-jauh hari. Lagipula aku memang ingin mengajaknya
secara spontan, sekaligus mengucapkan selamat wisuda secara langsung. Bagiku,
bertatap muka tetap lebih menyenangkan apalagi saat merayakan momentum
kehidupan.
Sore hari seusai wisuda, aku pergi ke tempat bimbingan
belajar. Setelah tiada lagi jadwal sekolah, jadwal les intensif memang efektif.
Hari itu, aku masuk kelas intensif terlalu awal, jadilah aku seorang diri
menikmati pendingin ruangan kelas. Sepuluh menit kemudian, beberapa kawan mulai
berdatangan dan mengisi kursi. Mereka kawan-kawan lama yang sudah sekelas
denganku sejak semester baru. Eh tunggu, siapa perempuan yang mengintip di
balik pintu kelas itu? Setelah beberapa detik berlalu, perempuan itu akhirnya
masuk dan air mukanya lega melihat guru belum tiba. Eh, lah, itu Putri!
“Put,” panggilku sambil menunjukkan kursi kosong di
belakangku.
“Eh, Bud,” balasnya sambil tersenyum dan agak
terkejut.
Putri duduk di kursi belakangku, menaruh ranselnya,
dan mulai mengajak bicara, “Kebetulan banget sekelas.”
“Iya. Emang kamu ngga beberes keluar kos?”
“Ngga, aku keluar kos pas kalau udah kelar ujian aja.
Aku baru banget daftar masuk kelas ini seminggu yang lalu, eh taunya kita
sekelas.”
“Oh gitu. Kamu udah mantep milih jurusan belum?”
“Udah, Bud. Doain ya aku bisa masuk psikologi, farmasi, kalau ngga statistika.”
“Aamiin. Mantap, Put. Terus mau di kampus mana itu?”
Putri mengeluarkan ponselnya dan menyalakan layar
depan. “Kampus ini nih, Bud.”
Aku agak memiringkan kepala lalu berkata “Eh, sama!”
“Beneran? Wih bisa satu sekolah lagi kita.”
“Iya. Hahaha. Hmm, kalau terkabul beneran sekampus,
kutraktir mi ayam deket sekolah deh, mau ngga?”
“Wah boleh, seru tuh, tapi nanti mi ayamku ngga pake
micin ya.”
“Hah? Kenapa ngga pake?” Sisi pengabdi micinku heran,
merasa tidak sesuai logika.
“Ya... kan ngga pake micin rasanya udah enak.” Aku
menaikkan kedua alis tanda heran lalu disusul tawanya pelan. Guru les datang
dan aku balik kanan, bersiap belajar di kursiku.
Aku belum tahu pasti arti kalimat terakhir Putri.
Namun, yang pasti, mulai hari ini aku berjuang menuju dan berada di tempat yang
sama dengannya. Kisah yang masih harus dilalui enak tak enaknya. Ah, jangan
mikir tak enak dululah toh hari pertama les intensif ternyata aku sesemangat
ini. Mungkin dengan adanya orang lain, belajar yang biasanya hambar akan terasa
menyenangkan, seperti Putri yang ingin mi ayamnya ngga pake micin. Yah, masuk
akal sih kalau keberadaan seseorang bisa mengubah sugesti orang lain. Bentar.
Jangan-jangan... eh?!
@30haribercerita
#30haribercerita
#hbc162020 #hbc152020 #hbc192020 #hbc172020 #hbc072020 #hbc062020 #hbc252020 #hbc262020 #hbc272020 #hbc282020 #hbc292020